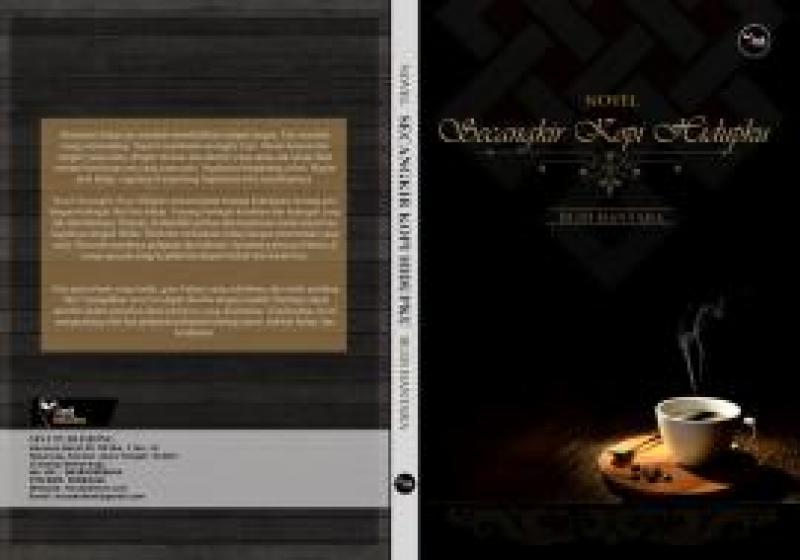SECANGKIR KOPI HIDUPKU # 4
Administrator 11 Agustus 2019 13:23:31 WIB
Hari mulai gelap. Aku mengantar pacarku melintasi jalan berbatu. Rimbunnya pepohonan di kanan kiri jalan membuat kegelapan semakin pekat. Listrik belum masuk desa Jurug kecamatan Pitu kabupaten Ngawi pada saat itu. Apalagi rumah pacarku yang berada di pinggir hutan jati dekat perbatasan Jawa Tengah, lebih mengerikan lagi. Desa di pinggir hutan itu belum tersentuh pembangunan. Jalan berbatu dan sebagian berlobang menyebabkan desa itu semakin sulit dijangkau. Aku tak sanggup mengayuh sepedaku sehingga kami terpaksa harus berjalan kaki. Namun pacarku tak mengeluh walau harus menempuh perjalanan seberat itu. Sesungguhnya aku tak sampai hati melihat pacarku menderita seperti ini.
“Maaf ya. Kita harus jalan.”
“Tidak apa-apa. Aku sudah biasa jalan kaki setiap hari.”
“Kamu tak menyesal menjadi pacarku yang hanya mempunyai sepeda jelek ini?”
“Saat ini kita hanya butuh cinta dan kesetiaan.” Dia meyakinkanku. Hatikupun berbunga-bunga. Kami berhenti sejenak. Kupeluk dia dengan cinta yang bergelora. Diapun memelukku dan aku menciumnya. Itulah pertamakalinya aku mencium seorang kekasih. Seketika terucap janjiku di dada untuk mencintainya selamanya.
“Semoga cinta kita abadi selamanya.”
Angin malam seolah berhenti. Gemuruh dalam dada semakin riuh. Dengan cinta dan semangat yang besar, sepeda kukayuh. Walaupun keringat bercucuran aku tak merasa lelah. Pelukan erat pacarku membuatku semakin merasa memiliki tenaga ekstra. Setelah menyusuri jalan gelap berbatu beberapa kilometer, akhirnya sampai juga di rumah pacarku. Lampu minyak kecil tak mampu menyinari seluruh ruang di rumah itu. Calon ibu mertuaku menyambut dengan ramah.
“Bagaimana keadaan ayah?” tanyanya antusias.
“Parah. Kurus sekali.” Jawab pacarku tanpa basa basi
“Sakit apa?”
“Kanker pembuluh darah.” Jawabku pelan tapi mengejutkan. Melihat raut wajah kesedihanku, calon ibu mertuaku tak melanjutkan pertanyaannya. Dia segera mengalihkan pembicaraan. Sementara pacarku menyodorkan segelas air putih sebagai pelepas dahaga.
“Air putih.”
“Terima kasih.” Akupun segera meminumnya.
“Buatkan kopi.” Perintah ibunya pada pacarku.
“Aku merebus air dulu, tapi ibu yang membuat kopinya.” Pintanya manja. Ibunya tersenyum dan mengikuti langkah putrinya ke dapur. Tak lama kemudian pacarku sudah kembali dengan membawa secangkir kopi panas. Senyumnya merekah sembari meletakkan kopi di depanku.
“Diminum Mas. Kalau kurang manis bisa ditambah gula.”
“Terima kasih. Apapun yang dihidangkan dengan cinta pasti nikmat.”
“Mas bisa saja.” Senyum manjanya membuat cintaku semakin berbunga-bunga.
“Sungguh. Kopi ini juga pasti nikmat.” Sambil meneguk kopi hitam manis yang nikmat kupandang wajah cantik pacarku.
“Benar-benar nikmat.” Ucapku sambil terus memandangi wajah cantik pacarku. Diapun menebarkan senyumnya yang penuh pesona.
Sejak saat itu banyak yang telah berubah dalam hidupku. Sedetikpun aku tak bisa melupakan bayangan Monica Anggraeni. Hari-hariku menjadi terasa semakin indah. Semua yang berhubungan dengan cinta pertamaku tak mungkin terhapus dari ingatanku. Senyumnya, tatap matanya, suaranya bahkan secangkir kopinya telah memberi warna dalam hidupku. Cinta telah mengajari aku untuk lebih mensyukuri keagungan Tuhan sebagai sumber segala cinta.
Senja masih memerah ketika saudaraku datang. Rumah kontrakanku yang terletak di jalan Ronggowarsito gang Wilis itu menjadi saksi bisu kecemasanku. Belum sempat kutanyakan keadaan ayah, kalimat yang diucapkan saudaraku sudah menyeretku ke puncak kegelisahan. Walaupun nada ucapannya lembut tetapi membuat jantungku berdegup kencang.
“Kamu harus pulang sekarang. Ayah menunggumu.”
“Ayah kritis?” tanyaku cemas.
“Tidak. Jangan cemas! Ayah hanya kangen.” Ucapan itu pasti hanya untuk menenangkan batinku yang penuh kecemasan. Aku takut kehilangan ayah. Tanpa membuang waktu kami segera berangkat. Sepeda motor melaju kencang membelah jalan raya. Dalam waktu sekejap aku telah sampai di depan rumah. Dengan langkah terburu-buru aku masuk kamar ayah. Ibu terkejut saat melihatku masuk.
“Saya datang ayah.” Kugenggam tangannya yang lunglai dan kucium penuh keharuan rasa. Ayah membuka matanya dengan tatapan teduh. Walaupun tak berdaya, ayah berusaha menunjukkan wajah tegar padaku. Ayah selalu mengajarkan pada kami untuk senantiasa tegar dalam memanggul salib kehidupan.
“Jangan menangis.” Jemarinya mengusap air mataku yang jatuh di pipi dengan penuh kasih.
“Saya takut.” Jawabku dengan isak tangis yang tak bisa kutahan. Siapapun mungkin merasa takut menghadapi kematian. Apalagi kematian diri kita sendiri atau kematian orang yang kita cintai. Rupanya ayah membaca pikiranku. Dalam keadaan tak berdaya, ayah brusaha meneguhkan hatiku dengan sisa-sia kebijaksanaan yang dimiliki.
“Manusia tak perlu takut menghadapi kematian asal dalam hidupnya melakukan kebaikan dan kebenaran. Kematian justru harus disyukuri karena akan membuka jalan menuju surga. Tanpa kematian kita tak akan bisa berjumpa Bapa di surga.”
“Tapi saya takut kehilangan ayah. Ayah harus sembuh.”
“Ambilkan obat ayah. Ini obat terakhir yang harus kuminum.”
“Pelan-pelan ayah. Aku mengangkat kepala ayah dan kusandarkan di dadaku. Walaupun hanya sebutir obat berukuran kecil, ayah sangat kesulitan menelan. Tenggorokannya semakin hari semakin tak berfungsi. Suaranyapun semakin tak jelas kudengar. Namun dengan susah payah terus mengajak kami berbicara. Ibu dan saudaraku hanya terpaku memandang ayah dalam pelukanku.
“Jika ayah dipanggil Tuhan, kalian harus rukun. Jaga ibu agar ayah tenang di surga.”
“Jangan khawatir ayah.”
“Untuk kamu Wan..., ayah minta maaf tak bisa menunggu pernikahanmu. Jangan pernah menyesal atas segala pilihan hidupmu.”
“Ayah jangan bilang begitu.” Air mataku yang membanjiri pipi semakin tak terbendung. Aku merasakan setiap ucapan ayah, akan menjadi pesan terakhir yang kudengar.
“Jangan pernah takut menghadapi sesuatu yang belum pasti terjadi. Hidup kalian tidak akan damai jika dihantui perasaan takut.”
“Iya ayah.”
“Sekarang kalian doakan rosario untuk ayah. Ayah ingin tidur biar nyenyak.”
“Baiklah ayah.” Aku menoleh ibu dan saudaraku yang selalu tekun berdoa. Ibu dan saudaraku juga selalu mengajariku untuk tabah memanggul salib kehidupan. Kamipun melakukan doa bersama seperti yang diminta oleh ayah. Selesai doa rosario dan novena tiga salam maria, ayahpun tertidur pulas. Kutinggalkan ibu di kamar menjaga ayah. Aku berdua bersama saudaraku, duduk di depan. Tak ada percakapan diantara kami. Kesunyian menjerat kami beberapa saat lamanya. Namun suara ibu, tiba-tiba membuatku tersentak.
“Ayahmu Wan...” mendengar suara ibu memanggilku, kami berdua segera berlari. Kulihat jam dinding di kamar itu menunjukkan jam 21.05 WIB. Ayah telah dipanggil Bapa di surga. Melihat wajahnya yang damai dalam hatikupun mengucapkan selamat jalan untuk ayahku. Semoga arwahnya diterima di sisi Bapa di surga. Saudaraku mencatat peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Agustus 1991.
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini |          |
| Kemarin |          |
| Pengunjung |          |
- MUSKAL KHUSUS DALAM RANGKA PENETAPAN KPM BLT-DD TAHUN 2026
- MUSKAL PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN BUMDESA MUGEN ARTO KALURAHAN PETIR
- KAPOLRES GUNUNGKIDUL KUNJUNGI KALURAHAN PETIR
- Apel Senin Pagi Pemerintah Kalurahan Petir
- Apel Senin Pagi Lurah dan Pamong Petir
- Hari Desa Nasional Tahun 2026
- APEL HARI DESA NASIONAL DI PENDOPO BALAI KALURAHAN PETIR